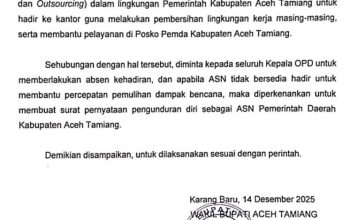AtjehUpdate.com,- Aceh Tamiang |
Anak itu tidak membawa proposal.
Tidak ada kop surat.
Tidak pula stempel basah bertuliskan darurat bencana.
Ia hanya membawa dua tangan kecil—satu menadah, satu lagi memegang harapannya sendiri.
Sudah 26 hari tercatat pasca banjir bandang. Angka itu terdengar rapi. Administratif. Nyaman di laporan. Tapi di jalan lintas Medan–Banda Aceh, di Karang Baru, waktu tidak dihitung dengan kalender. Waktu dihitung dengan lapar. Dengan berapa kali roti datang. Dan berapa lama perut bertahan tanpa janji, Sabtu, 13 Desember 2025
(Pasca Banjir Bandang, Hari ke-26 )
Seorang perempuan di balik kaca mobil menurunkan jendela. Tangannya keluar, menyerahkan sebungkus roti. Adegan itu singkat, nyaris banal. Namun di situlah satir bekerja dengan halus: negara mungkin datang dengan data, tapi kasih datang dengan refleks.
Anak itu menerimanya tanpa pidato terima kasih. Ia belum belajar retorika. Ia hanya tahu satu hal penting: roti bisa dimakan. Banjir tidak bisa diperdebatkan. Air sudah pergi, tapi lapar rupanya menetap.
Kita sering berkata, fase tanggap darurat sudah selesai. Kalimat itu terdengar tegas, seperti palu sidang. Tapi anak ini belum pernah diundang ke ruang rapat. Baginya, darurat tidak mengenal fase. Ia mengenal hari ini dan besok—jika besok masih ada roti.